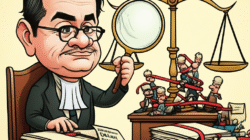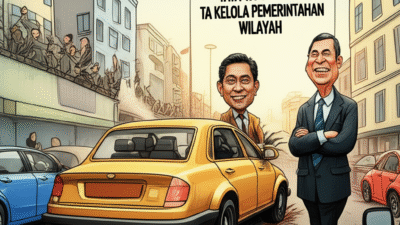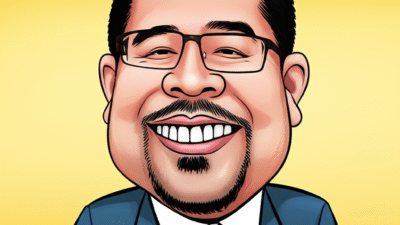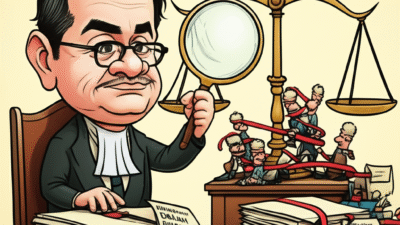Pemerintah sebagai Arsitek Keadilan: Mengukuhkan Kedudukan dalam Penangkalan Kekerasan terhadap Wanita
Pendahuluan
Kekerasan terhadap wanita adalah salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling merajalela dan memprihatinkan di seluruh dunia. Ia tidak mengenal batas geografis, sosial, ekonomi, maupun budaya. Dari kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, perdagangan orang, hingga praktik-praktik diskriminatif yang merendahkan martabat perempuan, dampaknya menghancurkan tidak hanya individu, tetapi juga struktur sosial dan kemajuan suatu bangsa. Dalam konteks ini, kedudukan pemerintah menjadi sentral dan tak tergantikan. Pemerintah, dengan segala instrumen kekuasaan dan tanggung jawabnya, bukan sekadar fasilitator, melainkan arsitek utama dalam membangun sistem penangkalan yang kokoh, berkeadilan, dan berkelanjutan. Artikel ini akan mengulas secara mendalam peran krusial pemerintah dalam upaya menumpas kekerasan terhadap wanita, dari landasan hukum hingga implementasi konkret.
I. Landasan Hukum dan Komitmen Internasional: Pondasi Tanggung Jawab Negara
Kedudukan pemerintah dalam penangkalan kekerasan terhadap wanita berakar kuat pada landasan hukum nasional dan komitmen internasional yang telah diratifikasi. Ini bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan kewajiban konstitusional dan moral:
- Konstitusi (UUD 1945): Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk hidup aman dan tenteram serta bebas dari ancaman kekerasan. Pasal 28H ayat (2) menegaskan hak setiap orang untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus guna memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Ini secara implisit menuntut negara untuk melindungi kelompok rentan, termasuk wanita, dari kekerasan.
- Undang-Undang Nasional:
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT): Undang-undang ini secara spesifik mendefinisikan bentuk-bentuk KDRT, mengatur hak-hak korban, kewajiban pelaku, serta peran pemerintah dan masyarakat. Ia mewajibkan pemerintah untuk menyediakan rumah aman, layanan kesehatan, dan bantuan hukum bagi korban.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS): Ini adalah terobosan monumental yang mengakui dan mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual, melindungi korban, mengatur pemulihan, serta memperberat sanksi bagi pelaku. UU TPKS menuntut pemerintah untuk membentuk unit pelayanan terpadu, memberikan bantuan hukum, psikologis, dan medis.
- Undang-Undang lainnya: Seperti UU Perlindungan Anak, UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya, semuanya mendukung kerangka kerja perlindungan wanita.
- Komitmen Internasional: Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional, termasuk:
- Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW): Ratifikasi CEDAW melalui UU No. 7 Tahun 1984 mengikat negara untuk mengambil langkah-langkah konkret, termasuk legislasi dan kebijakan, untuk menghapus diskriminasi dan kekerasan terhadap wanita.
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM): Mengakui martabat dan hak yang setara bagi semua manusia, termasuk hak untuk bebas dari kekerasan dan penyiksaan.
Landasan hukum ini menjadi mandat bagi pemerintah untuk tidak hanya bereaksi terhadap kasus kekerasan, tetapi juga proaktif dalam mencegahnya.
II. Pilar-Pilar Peran Pemerintah dalam Penangkalan Kekerasan
Peran pemerintah dalam penangkalan kekerasan terhadap wanita terbagi dalam beberapa pilar strategis yang saling menguatkan:
-
Pencegahan (Prevention): Mengurai Akar Masalah
- Edukasi dan Kampanye Publik: Pemerintah wajib meluncurkan kampanye kesadaran yang masif dan berkelanjutan untuk mengubah norma sosial yang bias gender, menormalisasi kekerasan, atau menyalahkan korban. Ini mencakup pendidikan seksualitas yang komprehensif, promosi kesetaraan gender sejak dini di sekolah, dan penyebaran informasi tentang hak-hak perempuan.
- Penguatan Kapasitas Masyarakat: Melalui program pemberdayaan ekonomi perempuan, penguatan kelompok masyarakat sipil, dan pelatihan bagi tokoh agama/adat, pemerintah dapat membangun ketahanan komunitas terhadap kekerasan.
- Penyusunan Kebijakan Pro-Perempuan: Mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap kebijakan pembangunan, mulai dari perencanaan kota yang aman, akses transportasi, hingga kebijakan ketenagakerjaan yang adil, adalah bentuk pencegahan struktural.
-
Perlindungan (Protection): Jaring Pengaman Darurat
- Penyediaan Layanan Darurat: Pemerintah harus memastikan ketersediaan layanan hotline 24 jam (misalnya, SAPA 129 Kemen PPPA), rumah aman (shelter) yang layak dan mudah diakses, serta pos pengaduan di tingkat desa/kelurahan.
- Respons Cepat Aparat Penegak Hukum: Kepolisian dan lembaga terkait wajib memiliki unit khusus yang terlatih untuk menangani kasus kekerasan terhadap wanita dengan sensitivitas dan profesionalisme, memastikan korban mendapatkan perlindungan segera dan tidak dire-viktimisasi.
- Perlindungan Saksi dan Korban: Menyediakan perlindungan fisik dan psikologis bagi korban dan saksi agar mereka merasa aman untuk melapor dan bersaksi tanpa intimidasi.
-
Penanganan dan Penegakan Hukum (Law Enforcement): Memastikan Keadilan
- Investigasi yang Berpihak pada Korban: Aparat penegak hukum (Polri, Kejaksaan) harus dilatih untuk melakukan investigasi yang tidak menghakimi, mengumpulkan bukti dengan cermat, dan memahami trauma korban.
- Proses Peradilan yang Adil: Pemerintah melalui lembaga peradilan harus memastikan proses hukum berjalan cepat, transparan, dan memberikan keadilan bagi korban. Ini termasuk pengangkatan hakim dan jaksa yang memiliki sensitivitas gender.
- Sanksi yang Tegas: Memastikan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai undang-undang, serta tidak ada impunitas bagi pelaku kekerasan.
- Bantuan Hukum Gratis: Menyediakan akses bantuan hukum gratis bagi korban yang tidak mampu agar hak-hak mereka terpenuhi dalam proses hukum.
-
Rehabilitasi dan Pemulihan (Rehabilitation & Recovery): Mengembalikan Harapan
- Dukungan Psikologis dan Medis: Pemerintah wajib menyediakan layanan konseling psikologis, psikiatri, dan medis (termasuk visum dan penanganan trauma) secara gratis dan rahasia bagi korban.
- Reintegrasi Sosial dan Ekonomi: Membantu korban untuk kembali berdaya secara sosial dan ekonomi, misalnya melalui pelatihan keterampilan, modal usaha, atau dukungan untuk kembali ke sekolah/pekerjaan, agar mereka tidak lagi bergantung pada pelaku atau menjadi rentan.
- Program Pasca-Penahanan Pelaku: Mengembangkan program rehabilitasi bagi pelaku untuk mencegah residivisme, meskipun fokus utama tetap pada korban.
-
Koordinasi dan Kolaborasi Multisektoral:
- Sinergi Antar Lembaga: Pemerintah harus menjadi koordinator utama antara berbagai kementerian/lembaga (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM, Polri, Kejaksaan, Pengadilan) untuk menciptakan respons yang terpadu dan tidak terfragmentasi.
- Kemitraan dengan Masyarakat Sipil: Mengakui dan mendukung peran penting organisasi masyarakat sipil (LSM) yang seringkali menjadi garda terdepan dalam penanganan kasus kekerasan. Kemitraan ini mencakup dukungan dana, fasilitas, dan legitimasi.
- Penguatan Data dan Riset: Pemerintah harus berinvestasi dalam pengumpulan data yang akurat dan komprehensif tentang kekerasan terhadap wanita untuk mengidentifikasi tren, mengevaluasi efektivitas program, dan merumuskan kebijakan berbasis bukti.
III. Tantangan dan Harapan ke Depan
Meskipun kedudukan pemerintah sangat sentral, implementasinya tidak lepas dari tantangan:
- Budaya Patriarki dan Stigma: Norma budaya yang masih menempatkan wanita sebagai objek atau menyalahkan korban seringkali menghambat pelaporan dan proses hukum.
- Keterbatasan Sumber Daya: Anggaran, jumlah tenaga ahli (konselor, psikolog, penyidik), dan fasilitas yang memadai masih menjadi kendala di banyak daerah.
- Kurangnya Sensitivitas Gender: Beberapa aparat penegak hukum atau birokrat masih kurang memahami perspektif gender, yang bisa berujung pada re-viktimisasi korban.
- Jangkauan Layanan: Layanan yang berpusat di kota besar belum tentu dapat diakses oleh korban di daerah terpencil.
Namun, harapan selalu ada. Dengan terus memperkuat komitmen politik, meningkatkan alokasi anggaran, mengembangkan kapasitas sumber daya manusia yang berperspektif gender, serta membangun partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, pemerintah dapat semakin mengukuhkan kedudukannya sebagai arsitek keadilan.
Kesimpulan
Kedudukan pemerintah dalam penangkalan kekerasan terhadap wanita adalah esensial dan tak dapat ditawar. Ini adalah cerminan dari komitmen negara terhadap perlindungan hak asasi manusia dan pembangunan yang inklusif. Dari merancang undang-undang, membangun sistem pencegahan, menyediakan jaring pengaman perlindungan, memastikan keadilan melalui penegakan hukum, hingga memulihkan trauma korban, pemerintah adalah tulang punggung dari seluruh upaya ini. Membangun benteng perlindungan yang kokoh dan keadilan yang merata bagi setiap wanita bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga investasi besar bagi masa depan bangsa yang beradab dan berkeadilan. Pemerintah harus terus menjadi garda terdepan, bukan hanya dalam menumpas kekerasan, tetapi juga dalam menciptakan masyarakat di mana setiap wanita dapat hidup bebas dari rasa takut dan dengan martabat penuh.